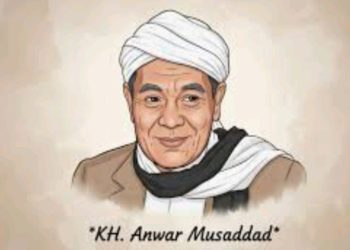Gelombang kegiatan tanam pohon tengah marak di Bojonegoro. Dari komunitas warga, pelajar, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintah, aksi tanam pohon kerap menjadi agenda bersama yang menandai kepedulian terhadap lingkungan. Namun di tengah euforia tersebut, muncul sebuah pengingat penting: menanam pohon tidak boleh berhenti sebagai tren musiman.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menegaskan bahwa gerakan menanam pohon semestinya melampaui sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, aksi ini harus tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup yang mentradisi, tertanam dalam keseharian masyarakat, bukan hanya hadir ketika ada momentum tertentu atau agenda formal.
“Pelan-pelan, tren ini harus menjadi tradisi” ucap Abdulloh Umar pada Jurnaba (25/1/2026).
Lebih jauh Ketua DPRD Bojonegoro itu menjelaskan, adanya tren menanam pohon, secara umum, sudah amat bagus. Namun, lebih utama lagi jika tidak berhenti pada tren. Melainkan harus menjadi semacam tradisi. Sebab, kata dia, tren bisa hilang kapanpun karena terganti tren lainnya. Sementara tradisi lebih awet dan bertahan lama.
Pesan dari Abdulloh Umar, menjadi refleksi kritis atas kecenderungan gerakan lingkungan yang selama ini kerap berhenti pada simbol. Pohon ditanam, foto diambil, lalu perhatian beralih ke isu lain. Padahal, makna ekologis sebuah pohon justru terletak pada proses panjang setelah penanaman: perawatan, perlindungan, dan keberlanjutan ruang hidupnya.
Databox Ekologi yang dihimpun tim riset Jurnaba menyatakan, Bojonegoro sesungguhnya punya tradisi menanam pohon sejak lama. Terutama di kawasan bukit kapur dan pinggiran sungai Bengawan. Menanam pohon, bagi masyarakat di kawasan tersebut, menjadi sebuah sarat uborampe (instrumen pelengkap) dalam memperingati musim tanam ataupun peralihan musim.
Dalam konteks Bojonegoro—wilayah yang secara historis dan ekologis bergulat dengan isu air, hutan jati, dan perubahan bentang alam—menanam pohon sejatinya bukan hal baru. Tradisi ekologis masa lalu telah lama mengenal relasi intim antara manusia dan vegetasi. Pohon bukan sekadar objek hijau, melainkan penyangga kehidupan: menjaga mata air, menahan erosi, menyediakan pangan, hingga menjadi penanda ruang sosial.
Karena itu, pesan Abdulloh Umar dapat dibaca sebagai ajakan untuk mengembalikan etika ekologis ke dalam laku hidup sehari-hari. Menanam pohon bukan hanya soal berapa bibit yang masuk ke tanah, tetapi sejauh mana kesadaran ekologis itu hidup dalam cara manusia memperlakukan lingkungannya. Menanam pohon sebagai tradisi, berarti menjadikannya praktik berulang lintas generasi—ditanam di halaman rumah, di tepi sungai, di ruang publik, dan dalam kesadaran kolektif.
Tradisi semacam ini tidak lahir dari instruksi sesaat, melainkan dari pembiasaan, keteladanan, dan pemahaman bahwa lingkungan bukan warisan leluhur semata, melainkan titipan untuk masa depan. Di tengah krisis ekologis yang kian nyata, Bojonegoro membutuhkan lebih dari sekadar tren hijau. Ia membutuhkan budaya merawat, di mana menanam pohon adalah awal dari hubungan panjang antara manusia dan alam—hubungan yang dijaga, dirawat, dan diwariskan.