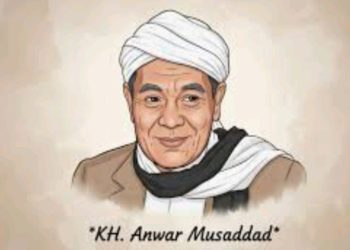Kita merasa sedang melawan kekuasaan, padahal sedang merawatnya. Kita bangga jadi warga kritis. Namun lupa, siapa yang merancang panggung kritik itu sejak awal.
Ruang itu mendadak terasa sempit, bukan karena jumlah kursi atau sorot kamera, melainkan oleh deretan pilihan yang berjatuhan seperti palu godam. Sumpah—ini bukan sekadar “ngekek”. Seorang guru besar UGM, simbol akal sehat dan ketenangan akademik, dipanggang habis di atas bara tanya-jawab. Dan Puthut EA, dengan senyum khas seorang boss Mojok yang tahu persis ke mana arah permainan, menyajikan menu yang tampak jenaka tapi sesungguhnya brutal: pilihan-pilihan yang tak memberi ruang untuk bernapas.
Mas Uceng memilih: AHY atau Gibran?
SBY atau Megawati?
Golkar atau Gerindra?
Dasco atau Sjafrie Sjamsoeddin?
Jokowi atau Prabowo?
Anies atau Ganjar?
Menteri atau anggota DPR?
Bahlil atau Pigai?
Di permukaan, semua itu terdengar seperti roasting ringan—hiburan politik yang mengundang tawa penonton. Namun siapa pun yang cukup lama hidup di republik ini tahu: ini bukan lelucon. Ini adalah simulasi hidup itu sendiri. Sebuah latihan memilih di antara dua hal yang sama-sama tidak sepenuhnya kita inginkan. Seperti ditarik paksa ke bilik suara kehidupan, lalu diminta mencoblos dengan tangan gemetar, sambil sadar bahwa apa pun pilihanmu, ada pil pahit yang harus ditelan.
Demokrasi—terutama versi neo-liberalnya—memang bekerja dengan cara demikian. Ia jarang menawarkan kebahagiaan; yang ia sediakan adalah keterpaksaan yang dibungkus prosedur. Kita diajari untuk merayakan pilihan, padahal yang sering kita alami hanyalah penyempitan kemungkinan. Seolah hidup berkata: pilihlah, bukan karena kau percaya, melainkan karena sistem tak memberi alternatif lain.
Dari jawaban-jawaban Mas Uceng, orang bisa membaca peta batinnya: seorang pejuang demokrasi yang masih percaya bahwa aturan, betapapun cacatnya, harus ditegakkan demi kepentingan publik. Transparansi, akuntabilitas, hukum—kata-kata yang kini sering terdengar seperti mantra lama, diucapkan berulang agar kita lupa betapa rapuh maknanya dalam praktik. Ia percaya pada rule of law, meski sadar hukum kerap menjadi arena tawar-menawar, bukan keadilan yang netral.
Ia juga seorang intelektual Muslim, anak dari seorang kiai besar di Makassar. Di tubuhnya, iman dan rasionalitas tidak selalu berdamai, tapi dipaksa berjalan beriringan. Ia meyakini syariat harus ditegakkan—sebuah keyakinan yang bagi sebagian orang terdengar luhur, bagi sebagian lain terasa mengancam. Figur-figur dengan komposisi semacam inilah yang sejak lama mewarnai sejarah pergolakan politik dunia: kaum terdidik, bermoral, yakin bahwa ada kebenaran yang harus dimenangkan, bahkan bila harus mengguncang rezim yang sedang berkuasa.
Dengan jargon demokrasi, mereka menjatuhkan apa yang disebut sebagai otoritarianisme. Di negeri ini, kita mengenal dua nama besar dalam daftar itu: Soekarno dan Soeharto. Keduanya tumbang dengan narasi yang sama—demi kebebasan, demi rakyat, demi masa depan. Namun sejarah, seperti biasa, gemar bermain ironi.
Ketegangan geopolitik global yang memuncak hari-hari ini perlahan membuka tabir yang lama disembunyikan. Selama hampir tujuh dekade, penggulingan rezim yang dicap otoriter ternyata kerap menjadi bagian dari modus hegemoni Amerika Serikat. Demokrasi dijadikan komoditas moral, disebarkan lewat jaringan kelas menengah intelektual, agar jalan bagi para pemodal besar menguasai institusi negara terbuka lebar. Negara dijinakkan, pasar dilepaskan, dan kedaulatan dipreteli dengan senyum prosedural.
Maka sesi “pilihan ganda” itu bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin. Kita semua, seperti guru besar di kursi panas itu, sedang terus-menerus dipaksa memilih. Bukan antara baik dan buruk, melainkan antara pahit dan lebih pahit. Dan mungkin, di situlah tragedi terbesar demokrasi modern: ia mengajarkan kita untuk merasa berdaulat, sambil perlahan melatih kita menerima keterpaksaan sebagai takdir.
Pada akhirnya, kita pulang dari tontonan itu dengan tawa yang belum sepenuhnya padam, tapi hati yang diam-diam digerogoti tanya. Sebab yang dipertontonkan bukan keberanian memilih, melainkan kepatuhan untuk terus memilih di dalam kandang yang sama. Demokrasi mengajari kita cara menjawab, bukan cara menolak pertanyaan. Ia memaksa kita percaya bahwa suara kita penting, sambil memastikan pilihan kita tak pernah benar-benar bebas.
Barangkali di situlah letak tamparannya: kita merasa sedang melawan kekuasaan, padahal sesungguhnya sedang merawatnya. Kita bangga menjadi warga kritis, namun lupa bertanya siapa yang merancang panggung kritik itu sejak awal. Dan ketika semua opsi terasa pahit, sistem akan tetap menang—karena kita tetap memilih.