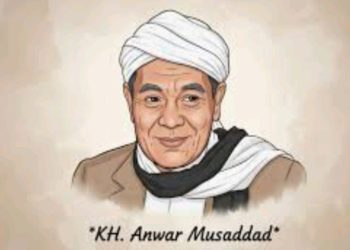Jika suatu hari kekuasaan terasa terlalu nikmat, barangkali itu pertanda bahaya: bukan karena mereka terlalu kuat. Tapi karena kita terlalu lama lupa bagaimana cara menarik jarum suntiknya.
Kekuasaan, kata orang-orang waras, seharusnya dijalani dengan jarak: cukup dekat untuk bekerja, cukup jauh untuk tidak mabuk. Namun sejarah—dan halaman depan koran setiap pagi—berulang kali membuktikan bahwa kekuasaan lebih sering diperlakukan seperti zat terlarang. Sekali mencicipi, tubuh ingin lagi. Sekali merasa berkuasa, sel-sel ikut bersorak.
Di ruang yang tak kasatmata, jauh di balik pidato, baliho, dan senyum resmi, kekuasaan bekerja diam-diam di tingkat yang paling purba: tubuh. Ia menyusup ke neuron, menggetarkan sirkuit penghargaan di otak, memanggil dopamin dengan cara yang sama seperti alkohol, heroin, atau kokain. Kekuasaan, terutama yang absolut dan tanpa pengawasan, adalah minuman keras paling mahal: ia memabukkan tanpa botol, membuat penggunanya merasa besar, penting, nyaris tak tersentuh.
Para ilmuwan menyebut dopamin sebagai biang keladi rasa senang. Nayef, dengan bahasa klinis yang dingin, menjelaskan bahwa kekuasaan mengaktifkan sirkuit penghargaan yang sama dengan narkoba. Tapi di luar laboratorium, temuan itu menjelma drama sosial: pejabat yang kehilangan empati, pemimpin yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri, keputusan-keputusan brutal yang lahir dari kepala yang terlalu lama dimahkotai.
Pada tahap awal, kekuasaan sering menyamar sebagai peningkatan fungsi kognitif. Pikiran terasa tajam, keputusan diambil cepat, suara terdengar lebih lantang. Tapi seperti semua candu, fase ini singkat. Hambatan runtuh, penilaian merosot, dan narsisme tumbuh seperti jamur di ruang lembap. Yang tersisa adalah keberanian palsu untuk melanggar batas—batas moral, batas hukum, bahkan batas kemanusiaan.
Di titik inilah kekuasaan berubah menjadi kecanduan penuh. Si pecandu tidak lagi memerintah; ia dikuasai. Ia akan menghalalkan apa saja demi mempertahankan sensasi itu: memelintir aturan, membungkam kritik, mengorbankan yang lemah. Rasa malu? Itu kemewahan bagi orang yang masih punya jarak dari candunya. Bagi pecandu kekuasaan, rasa malu hanyalah gangguan kecil yang harus disingkirkan.
Dan ketika kekuasaan mulai terancam—ketika kursi digoyang, ketika batas masa jabatan mendekat—tubuh bereaksi seperti pecandu yang dipaksa berhenti. Di tingkat seluler, keinginan membuncah. Penolakan terhadap kehilangan muncul bukan sebagai argumen rasional, melainkan sebagai kepanikan biologis. Kekuasaan, seperti zat adiktif lainnya, menciptakan ketergantungan yang menolak logika.
Di sinilah fiksi dan realitas saling menatap tanpa berkedip. Kita menyebutnya tragedi politik, krisis demokrasi, atau sekadar berita buruk. Padahal, mungkin ini juga kisah tentang tubuh manusia yang gagal diberi batas. Tentang dopamin yang tak pernah diajarkan etika. Tentang masyarakat yang lupa bahwa kekuasaan, jika tak diawasi, bukan sekadar alat—ia candu. Dan candu, seperti kita tahu, jarang berhenti dengan sukarela.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi mengapa mereka mencintai kekuasaan, melainkan mengapa kita membiarkan cinta itu tumbuh tanpa batas. Sebab setiap kecanduan selalu membutuhkan lingkungan yang permisif: penonton yang diam, hukum yang lentur, dan ingatan kolektif yang pendek. Kekuasaan yang memabukkan tidak lahir sendirian; ia dibesarkan oleh tepuk tangan, dinormalisasi oleh kebiasaan, dan dimaafkan atas nama stabilitas.
Maka mungkin yang perlu direhabilitasi bukan hanya para pemegang kuasa, tetapi juga kita sebagai masyarakat. Kita perlu belajar mencurigai figur yang terlalu lama duduk, terlalu sering dipuja, terlalu kebal terhadap kritik. Sebab dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya tidak memberi kenikmatan—ia harus melelahkan, membatasi, dan membuat gelisah. Jika suatu hari kekuasaan terasa terlalu nikmat, barangkali itu pertanda bahaya: bukan karena mereka terlalu kuat, melainkan karena kita terlalu lama lupa bagaimana cara menarik jarum suntiknya.[]